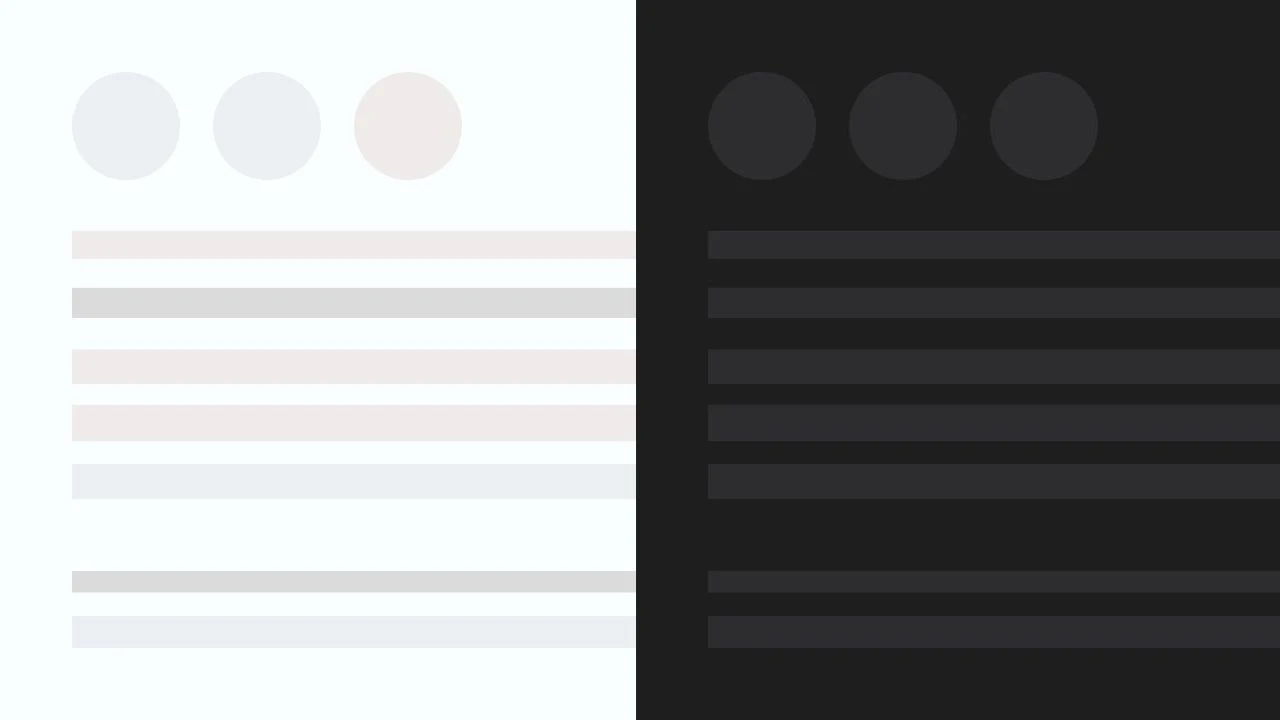Pada tanggal 25-27 November 2013, Rumah Budaya Noktah menyelenggarakan focus groupsdiscussion (FGD) bertema ‘Revitalisasi Kaba Menuju Seni Pertunjukan Modern’ bertempat di Hotel Hayam Wuruk, Padang. Dalam blog-nya Teater Noktah menyebutkan bahwa tujuan FGD itu adalah mendorong para pekerja teater ‘menerjemakan’kaba ke dalam bentuk lakon dengan cara-cara baru yang inovatif.
Sehingga repertoar sastra lisan Minangkabau itu dapat direvitalisasi dan menjadi menarik lagi bagi masyarakat umum. Implementasi dari FGD itu antara lain dipertunjukkan dalam ‘Minangkabau Arts Festival’ yang dihelat oleh Rumah Budaya Noktah dari 23 s/d 28 Desember di tiga kota: Padang, Payakumbuh, dan Sawahlunto.
Usaha Rumah Budaya Noktah ini mengingatkan saya pada satu artikel Umar Junus, “Kaba: an unfinished (his-)tory”, Tonan Ajia Kenkyu 32,3 (1994): 399-415. Dalam hal ini, saya tertarik pada kata ‘unfinished’ dalam artikel Umar Junus tersebut, sebab saya rasa riwayat kaba memang belum lagi tamat, dan itu dibuktikan dengan prakarsa Rumah Budaya Noktah yang telah menyelenggarakan FDG tersebut.
Gagasan mengartikulasikinikan kaba ke dalam genre teater modern menambah panjangnya jalan sejarah transformasi yang sudah dialami oleh salah satu khazanah lisan Minangkabau yang terkenal itu. Dalam esai ini saya ingin menelusuri kembali berbagai transformasi yang telah dialami oleh kabasepanjang dua abad terakhir sebelum memfokuskan perhatian lebih khusus pada adaptasi kaba ke dalam seni pertunjukan.
Eksistensi kaba Minangkabau mulai dipertanyakan menyusul terjadinya Perang Paderi (1803-1837). Kemenangan Kaum Agama di sebagian besar wilayah darek telah berakibat pula pada dunia seni. Kaum Agama (Paderi) mencoba menyingkirkan kaba–kaba dari masyarakat Minangkabau karena dianggap mengandung unsur paganisme dan menggantikannya dengan cerita-cerita yang mengandung ajaran Islam dan bernuansa Arab. Demikian catatan D. Gerth van Wijk dalam pengantarnya untuk terjemahan Kaba Puti Balukih dalam bahasa Belanda (lihat artikelnya: “De geschiedenis van Prinses Balkis (Hikajat Poeti Baloekih)”, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 41 (1881): i-95.
Penyebaran aksara Jawi sejak abad ke-17 tampaknya tidak banyak mempengaruhi kaba, dalam arti bahwa kehadiran aksara itu tidak mendorong kodifikasi kaba ke dalam bentuk tulisan secara signifikan. Sejauh penelurusan saya di berbagai perpustakaan di dunia, dapat dikesan bahwa tidak banyak naskah-naskah kaba yang dituliskan dalam aksara Jawi bertulisan tangan, kecuali beberapakaba terkenal seperti Kaba Cindua Mato (lih: Taufik Abdullah 1970) dan juga tambo.
Beberapa studi menunjukkan bahwa kebanyakan kaba yang ditulis tangan memakai aksara Jawi pada abad ke-18 dan 19 lebih didorong oleh beberapa sarjana Barat ketimbang atas kesadaran masyarakat pendukungnya sendiri. Para sarjana Barat, khususnya Belanda, berkepentingan untuk mendapatkan versi tulisan teks-teks pribumi tertentu yang mereka anggap mengandung unsur sejarah yang dapat digunakan untuk memahami aspek sosial dan historis suatu kelompok etnis. Di Minangkabau KabaCindua Mato mengandung unsur sejarah seperti itu, sehingga sarjana seperti J.L. van der Toorn mencoba mendapatkan kodifikasi tertulis kaba itu.
Namun keadaan relatif berubah setelah budaya cetak (print culture) diadopsi oleh masyarakat Melayu pada paroh kedua abad ke-19. Seiring dengan kemunculan penerbit-penerbit pribumi di kota-kota dan pusat bandar di kawasan ini, kaba juga mulai dicetak dan dibukukan. Dalam surat kabar-surat kabar lama sering ditemukan iklan buku-buku kaba tercetak ini. Aksara yang dipakai masih aksara Jawi, tapi memasuki abad ke-20 pelan tapi pasti aksara itu dialahkan oleh aksara Latin.
Sekarang kita melihat banyak kaba dikasetkan dan juga di-VCD-kan. Pengkasetan kaba untuk tujuan komersial sudah berlangsung sejak akhir 1980-an, sedangkan VCD komersial kaba mulai muncul sejak awal tahun 2000-an. Ada bukti yang menunjukkan bahwa di era gramofon (1890-an s/d 1960-an) beberapa kaba juga sudah pernah direkam dalam piringan hitam (gramophone disc).
‘Penerjemahan’kaba ke dalam bentuk seni drama sesungguhnya sudah dimulai sejak 1920-an. Ada yang mengatakan bahwa randai adalah arketip dari ‘penerjemahan’kaba ke dalam seni pertunjukan. Matthew Isaac Cohen dalam artikelnya “Look at the Clouds: Migration and West Sumatran ‘Popular’ Theatre”, New Theatre Quarterly 19,3 (2003): 214-229 mengatakan bahwa kelahiran randai terkait dengan kedatangan grup-grup musik dan seni pertunjukan dari Eropa (seperti grup-grup sirkus dan opera) dan grup-grup drama bangsawan dan komedi stambul di Padang pada akhir abad ke-19. Pada masa itu budaya bandar (urban culture) mulai berkembang di Padang akibat kemajuan ekonomi uang yang ditopang oleh beragam etnis pribumi, Asia lainnya (Cina, Keling, Arab), dan Eropa yang tinggal di ibukota Sumatras Westkust itu.
Ch. E.P. van Kerckhoff dalam artikelnya “Het Maleisch Toneel ter Weskust van Sumatra”, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde 31 (1886):302-14 mengatakan bahwa grup-grup musik dari luar itu telah memberikan inspirasi kepada orang Minangkabau untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam kesenian tradisional mereka. Randai dianggap sebagai bentuk inovasi itu, karena seni akting dikombinasikan dengan seni pencak yang sudah sedia ada dalam khazanah kebudayaan Minangkabau tradisional.
Cohen juga mengatakan bahwa budaya pasar malam (fancy fair) yang diciptakan Belanda juga mendorong inovasi dalam tanah kesenian Minangkabau sebab dalam acara pasar malam terbuka kesempatan untuk mempertunjukkan berbagai bentuk kesenian selain untuk promosi komoditas ekonomi dan kerajinan rakyat.
Menurut Cohen, pada tahun 1932 bentuk pertunjukan yang sekarang dikenal sebagai randai telah dipentaskan dalam acara pasar malam di Labuah Silang, Payakumbuh. Sedangkan laporan pertama mengenai randai secara luas muncul dalam majalah Pandji Poestaka tahun 1942.
Selanjutnya kaba tidak hanya ‘diterjemahkan’ dalam bentuk randai, tapi juga dalam bentuk drama atau teateristilah yang biasa dipakai sekarang. Salah satu bukti tertua mengenai proses ‘penerjemahan’kaba ke panggung teater adalah pertunjukan Kaba Cindua Mato oleh siswaKweekschool (Sekolah Raja) di Fort de Kock pada tahun 1925. A.A. Navis dalam bukunya AlamTerkembang jadi Guru (1985) mengatakan pertunjukan itu sebagai cikal bakal randai. Akan tetapi sejauh yang dapat saya kesan dari foto-foto pertunjukan itu (salah satunya diperlihatkan dalam ilustrasi) tidak terlihat adanya tarian pencak yang menjadi salah satu unsur randai. Hal ini membawa saya pada dugaan bahwa pertunjukan yang dipentaskan oleh siswa Sekolah Raja di Bukittingi itu adalah bentuk drama, bukan randai.
Pada dekade-dekade sesudahnya kaba makin sering didramakan. Salah seorang yang sering mengolah kaba menjadi drama pada tahun 1940-an dan 1950-an adalah Adnan Kapau (A.K.) Gani (1905-1968), seorang dokter dan politisi asal Minang penyuka dunia seni yang aktif dalam politik Indonesia di Zaman Pergerakan dan saat Republik Indonesia masih muda usia (lih:http://id.wikipedia.org/wiki/Adenan_Kapau_Gani).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejak sekitar 1920-an telah terjadi ‘penerjemahan’kabake dalam seni pertunjukan melalui dua bentuk: randai dan drama (teater). Lebih awal dari itu telah terjadi pula pengkodifikasian kaba dalam bentuk tulisan: dalam bentuk naskah bertulisan Jawi dalam jumlah yang terbatas dan dalam bentuk buku cetakan dalam jumlah yang lebih banyak.
Kegiatan Rumah Budaya Noktah yang telah menyelenggarakan FGD ‘Revitalisasi Kaba Menuju Seni Pertunjukan Modern’, yang tentunya diharapkan akan membuahkan hasil, menunjukkan bahwa ‘penerjemahan’kaba ke dalam seni pentas terus berlanjut dari masa ke masa.
Konsep monolog kaba, sebagaimana telah dipertunjukkan tgl. 25 Desember lalu di Hotel Hayam Wuruk, adalah salah satu dari berbagai alternatif pengartikualian kaba masa kini. Kita berharap para teater di Sumatra Barat akan menemukan berbagai alternatif lain, misalnya dengan mengawinkan berbagai genre seni, memanfaatkan media elektronik, dan lain sebagainya. Eksplorasi estetika baru terhadap kaba diharapkan akan dapat memperkaya konsep dan meningkatkan dinamika kehidupan teater modern di Sumatra Barat sekaligus untuk merevitalisasi dan melestarikan genre kaba sebagai khazanah kesusastraan Minangkabau.
Foto: KITLV Leiden
Sumber: Suryadi, alumnus FIB UNAND, dosen dan peneliti di Leiden University Institute for Area Studies, Belanda.